Belum lama ini terbit sebuah buku berjudul Al-Qur’an Kitab Toleransi yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi. Penulis buku ini gusar dengan fenomena menguatnya arus ideologi kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam bukunya, Zuhairi berharap dapat menyelamatkan al¬Qur’an dari ideologisasi dan fungsionalisasi ekstremisme.
Selanjutnya karya itu juga ingin meletakkan fungsi Al-Qur’an dalam kehidupan manusia sebagai ‘cahaya’ dan ‘petunjuk’. Ia lalu merujuk pada surah an-Nur: 35 ditegaskan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Penulis kemudian menafsirkan kata ‘bumi’ dalam ayat itu sebagai salah satu perhatian yang besar terhadap masalah ‘antroposentrisme’. Sementara kata ‘langit’ dimaknai penulis sebagai dimensi ‘teosentrisme’ yang harus berkait kelindan dengan bumi yang menyimbolkan antroposentrisme (hlm 92). Tetapi pada faktanya, penulis lebih berpihak pada klaim antroposentrisme.
Dalam tulisannya, tampak sekali Zuhairi sangat mengidolakan metode Hermeneutika yang diimpor dari tradisi interpretasi Bible dan filsafat Barat. Sepertinya ia cenderung kepada pemikiran sosok hermeneut, Paul Riccoeur (1913-2005 M). Zuhairi menilai, salah satu penyebab sebagian besar umat Islam bertindak intoleran adalah, karena terjebak dalam tafsir yang lebih berdimensi taklid daripada berdimensi hermeneutis (h.18). Zuhairijuga menekankan bahwa tak ada pilihan lain kecuali ‘membongkar tradisi tafsir’, yang semula hanya berkutat pada penjelasan menjadi pemahaman atas Al-Qur’an (hlm 124).
Teori tafsir itu mulai digugat dan ditantang oleh aliran-aliran hermeneutika filsafat pada abad ke 20. Problem isu hermeneutika filsafat kontemporer telah melontarkan berbagai diktum yang mengkritisi dan berambisi menjadi alternatif pintas bagi kebuntuan dan kebekuan penafsiran teks agama yang rigid, kaku dan kehilangan elan vital “maqashid syariah”.
Filsafat pemahaman lalu mengajukan tandingan terhadap teori tafsir.
Pertama, pemahaman teks adalah hasil perpaduan antara cakrawala pemahaman penafsir dengan cakrawala makna dalarn teks.
Kedua, upaya pemaharnan teks adalah proses tiada henti; seperti halnya pluralitas pemaharnan teks tidak mengenal batas-batas. Dengan demikian setiap terjadi perubahan dalarn diri penafsir berikut cakrawala pikirannya, maka dimungkinkan lahirnya pemahaman baru.
Ketiga, pra-konsepsi penafsir adalah syarat tercapainya suatu pemaharnan. Tak mungkin ada makna objektif tanpa melibatkan subjektifitas penafsir.
Keempat, tak ada pemaharnan yang tetap dan tidak berubah.
Kelima, tujuan penafsiran teks pada saat ini, bukan untuk menangkap maksud pengarang teks. Sebab, penafsir saat ini menghadapi sebuah teks, dan bukannya pengarang teks. Teks sebagai entitas yang mandiri, berdialog dengan penafsir sehingga melahirkan suatu pemaharnan, dengan demikian setiap penafsir tidak diharuskan mencari dan menangkap maksud dan tujuan yang ingin diungkapkan si pengarang teks.
Keenam, tak ada patokan dan standarisasi dalarn menilai salah atau benar suatu penafsiran. Karena sejatinya tidak ada tafsir yang benar dan tunggal. Hermeneutika filsafat mengakui otoritas penafsir dan mengabaikan tujuan pengarang sarna sekali.
Ketujuh, hermeneutika filsafat sesuai dengan teori relatifitas penafsiran, dan membuka ruang yang sangat luas bagi penafsiran¬penafsiran yang radikal sekalipun.
Dari ketujuh metode umum “pemaharnan” teks dalarn filsafat hermeneutika yang telah dipaparkan, terkuak dengan jelas ketidakcocokan teori filsafat pemaharnan ini dengan sifat dan karakter dasariah al-Qur’an seperti yang telah dijelaskan. Memang diakui luas oleh para pakar al¬Qur’an bahwa teks-teks kitab suci mengandung pelbagai kemungkinan makna dan pemaharnan sesuai kecenderungan ilmu yang dikuasai setiap mufasir.
Dalam bukunya, Zuhairi menyinggung fatwa MUI dalam Munas MOl tahun 2005. Menyitir pandangan tokoh pluralisme, Zuhairi menyebutkan fatwa MOl itu sangat simplistis dan mudah dipatahkan (hlm 210). Padahal pengertian pluralisme yang dimaksud oleh MOl adalah pengertian ilmiah dan filosofis yang berkembang dalam kajian filsafat agama.
Pluralisme dalam pengertian sosio-politis, sebagai sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, ras, suku, aliran maupun partai, bisa diterima dalam Islam. Yang diharamkan MUI, adalah paham yang khas dalam dunia keilmuan filosofis yang telah dirintis oleh John Hick dan para pengikutnya di dunia Islam seperti Sayyed H. Nasr, Rene Guenon, dan Fritchof Schuon dll.
Sangat jelas, rumusan Hick tentang pluralisme agama berangkat dari pendekatan substantif yang mengungkung agama dalam ruang privat yang sempit. la juga memandang agama sebagai konsep hubungan dengan kekuatan sakral yang bersifat metafisik ketimbang sebagai suatu sistem sosial.
Dalam pluralisme yang diusung Hicks, terdapat konsep “persamaan agama” (religous equality). Konsep ini tidak saja dalam memandang eksistensi ril agama-agama (equality of existence) namun juga dalam memandang aspek esensi dan ajarannya (syariat). Dengan demikian diharapkan tercipta kehidupan bersama antar agama yang harmonis, penuh toleransi, saling menghargai (pluralisme Agama).
Rumusan ini oleh MUI difatwakan haram untuk diikuti oleh umat Islam.
Akhirnya,perlu ditegaskan bahwa mengakui eksistensi praktis agama-agama lain yang beragam dan saling berseberangan ini, dalam pandangan Islam, tidak secara otomatis mengakui legalitas dan kebenarannya seperti yang diajarkan oleh kaum pluralis.
Sikap yang tepat adalah menerima kehendak Allah SWT dalam menciptakan agama-agama ini sebagai berbeda-beda dan Karena Allah swt telah menciptakan jagad raya dan segala isinya ini dengan bentuk dan kondisi yang sistematis dan seimbang; ada baik dan buruk, haq dan bathil, cahaya dan gelap, bahagia dan sengsara.
Kehendak llahiah ini ada dua macam, merujuk kepada istilah yang dipopulerkan Syekh Muhammad ‘Abduh (1849-1903 M), yaitu:
Pertama, kehendak ontologis (iradah kawniyyah) dan
Kedua, kehendak legalistis (iradah syar’iyyah). Di satu sisi, Allah SWT menciptakan sesuatu dan memang menghendakinya secara ontologis danlegalistis,seperti:kebaikan, kebenaran, iman, malaikat, dan segala sesuatu yang Dia cintai dan ridhai. Tapi di sisi lain, Allah SWT menciptakan sesuatu dan menghendakinya secara ontologis tapi tidak secara legalistis, seperti: kejahatan, kebatilan, setan, kekufuran dan segala sesuatu yang Dia benci.
Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan empat faktor yang melahirkan sikap toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non¬Muslim.
Pertama, keyakinanterhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaan dan kesukuannya. Kemuliaan ini mengimplikasikan hak untuk dihormati.
Kedua, keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas (ontologis) yang dikehendaki Allah SWT yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur,
Ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran, orang kafir atau menghukum kesesatan orang sesat. Allah SWT lah yang akan mengadili mereka di hari perhitungan kelak. (al-Hajj: 69, al-Syura: 15).
Keempat, keyakinan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berbuat Adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik (at- Taubah: 6). Begitu juga Allah SWT mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir (al-Maidah: 8). Demikianlah visi toleransi dalam perspektif Al-Qur’an.
Fahmi Salim, MA Alumnus S-2 Al-Azhar, Mesir
Daimbil dari majalah Al Mujtama
support by:
umroh-haji.net

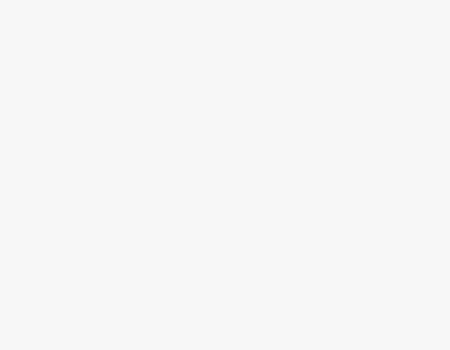

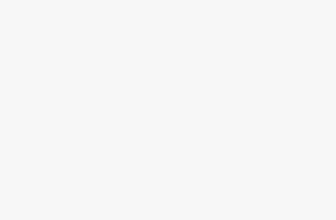



a good theme, and you can read more