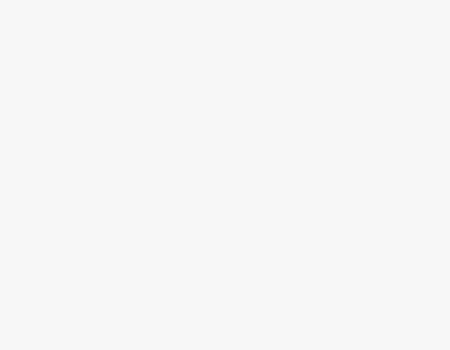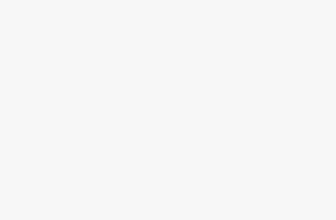Bagi orang Islam, menunaikan ibadah haji adalah karunia khusus, keni’matan, dan bahkan kebanggaan tersendiri. Berangkat ke tanah suci, ibaratnya berangkat menemui seseorang yang telah lama dirindukan. Luapan kerinduan yang mendalam diiringi bara iman yang menggejolak, meringankan langkah seorang Muslim menuju keridhaan Ilahi yang Rahman.
Betapa tidak, haji merupakan kewajiban yang memiliki konotasi sbb:
1. Memenuhi panggilan Ilahi. Melaksanakan suatu ajaran agama, apa saja wujudnya, adalah realita pemenuhan terhadap panggilan Allah. Namun ibadah haji memiliki konotasi khusus dengan panggilan ini. Oleh sebab itu, di saat seorang memulai niatnya untuk beribadah (ihram), ia diharuskan untuk mengucapkan “Labbaik Allahumma Labbaik” (Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah).
2. Ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima (terakhir). Sehingga dengan menunaikannya dapat diartikan sebagai pemenuhan terhadap keseluruhan ajaran Islam. Atau dengan kata lain, melakukan ibadah haji berarti pula seorang Muslim menyempurnakan keislamannya
3. Masdar (asal) kata haji, dapat juga melahirkan makna lain selain dari “hajjun atau hijjun” yang berarti haji. Makna tersebut adalah “hujjatun” yang berarti “tanda, bukti, alasan. Dengan demikian, haji dapat menjadi tanda kesempurnaan Islam, menjadi bukti akan keislaman, serta menjadi alasan bagi keselamatan seorang Muslim, dunia Akhirat.
4. Dari segi material, pelaku haji juga memiliki konotasi “kemampuan”, yang pada umumnya ditafsirkan sebagai kemampuan material. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa pelaku haji termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpunya (the haves).
5. Dengan predikat hajinya, seorang haji akan semakin termotivasi untuk mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Allah, sebab alangkah ganjilnya bila seseorang bergelar haji tapi keislamannya semakin semrawut. Shalat lima waktu tidak terjaga, zakat tidak terperhatikan, prilaku terhadap sesama semakin jauh dari norma-norma kislaman, dll.
Kelima hal tersebut di atas, antara lain, yang menjadikan seseorang bangga dengan predikat haji yang dimilikinya. Sebab memang wajar jika saat ini berhaji begitu terndy, serta cenderung dijadikna sebagai ukuran kesalehan, disamping merupakan prestise sosial bagi pemiliknya. Tentu disayangkan jika kemudian prediket “haji” dijadikan “taqiyah” alias pelindung pelakunya dari berbagai penyelewengan dan dosa yang dilakukannya. Artinya, terkadang seseorang semakin merasa aman untuk berbuat jahat, hanya karena bersembunyi di balik gelar haji yang dimilikinya.
Al Qur’an secara gamblang menyebutkan bahwa menunaikan ibadah haji dapat menghasilkan dua macam kebanggaan; dunia semata, dan ini yang sia-sia karena di Akhirat kelak pelakunya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Atau dunia-Akhirat, dan pelakunya kelak dapat terjaga dari kobaran api neraka (lihat S. Al Baqarah: 200-201, dan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang semuanya berhubungan dengan masalah-masalah haji). Dengan kata lain, bukanlah sesuatu yang keliru jika seseorang berhaji, disamping dalam rangka mencari nilai akhiratnya, sekaligus mencaru nilai duniawinya Hal ini digambarkan oleh Allah: “Tidaklah dilarang bagi kamu untuk mencari fadhilat Tuhanmu, maka jika kamu telah keluar dari Arafah maka ingatlah Tuhanmu di sisi Masy’aril haram” (Ayat). Yang keliru memang adalah jika haji dijadikan justifikasi atau pembenaran terhadap kecenderungan untuk menyeleweng.
Haji Sosial
Istilah haji sosial sesungguhnya bukanlah hal baru dalam pembahasan ibadah dalam Islam. Karena pada hakekatnya, keseluruhan ibadah ritual dalam agama Islam memiliki konsekwensi sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan lebih tegas, seolah-olah ibadah ritual yang tidak menghasilkan buah “kepedulian sosial” ibaratnya pohon yang tidak berbuah (lihat misalnya S. Al Ma’uun).
Shalat, yang dimulai dengan takbir “Allahu Akbar” menunjukkan bahwa hidup seorang Muslim itu didasarkan kepada relasi “Uluhiyah” yang kokoh atau pengabdian kepada Allah Yang Maha Besar (Al Akbar), dan memberikan efek sosial yang tinggi, menyebarkan perdamaian dan keselamatan (Salaam) bagi semua pihak, baik yang di kiri maupun yang di kanan.
Puasa adalah ibadah yang khusus hanya antara Allah dan hambaNya. “Puasa adalah bagiKu dan hanya saya yang membalasnya”. Namun implikasi sosialnya jelas, diharapkan dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi itu (makan, minum dan hubngan seksual), seseorang akan mampu merasakan perasaan metreka yang kurang beruntung. Sehingga wajar sekali jika seseorang, karane satu dan lain hal, tidak mampu melakukan ibadah puasa tersebut, harus menggantinya dengan “fidyah” (memberi makan kepada orang miskin).
Demikian halnya dengan dzikir, menyebut Asma Allah. Tanpa melahirkan bukti-bukti sosial, sia-sia jadinya, bahkan dapat membawa kemurkaan Ilahi. Ibnu Umar mengatakan “Mengagumkan Asma Allah tanpa memuliakan hamba-hambaNya, mendatangkan laknat bagi pelakunya”.
Ibadah haji, sebagai rukun Islam yang kelima, di samping menekankan nilai ritualnya, juga sarat dengan pesan-pesan sosial kemanusiaan, politik, hubungan internasional, perekonomian, dll. Sehingga wajar, sebagaimana disebut terdahulu, bahwa ayat-ayat yang berbicara mengenai ibadah haji dalam al Qur’an berhubungan erat dengan pembicaraan mengenaim kehidupan manusia secara luas.
Ibadah haji yang ditunaikan atas dasar “istitha’ah” (kemampuan) pada masa sekarang memiliki makna tersendiri. Jumlah penduduk miskin semakin bertambah, yang konsekwensinya semakin menambah kepedulian kita untuk membantu mereka. Sehingga sangat diharapkan bahwa ibadah haji tidak lagi dilakukan oleh jutaan manusia hanya sekadar tradisi ritual keagamaan semata, tapi hendaknya melahirkan sifat kepedualiaan sosial yang solid bagi pelakunya. Dengan kata lain, ibadah haji diharapkan tidak saja menumbuhkan kesalehan infiradi (individu), melainkan juga menyuburkan kesalehan jama’i (kesalehan sosial).
Haji Mabrur Tanpa Haji
Tersebutlah dalam suatu kisah sufi bahwa seseorang yang menunaikan ibadah haji tertidur lelap ketika wukuf di tengah teriknya matahari di padang Arafah. Dalam tidurnya ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Perasaan berjumpa dengan Rasulullah ini memberikan harapan dalam dirinya bahwa hajinya telah menjadi haji mabrur. Namun untuk kepastian, ia memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW: “Siapakah di antara mereka yang diterima hajinya sebagai haji mabrur wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW seraya menarik napas dalam-dalam, menjawab: “Tak seorangpun dari mereka yang diterima hajinya, kecuali seorang tukang cukur tetanggamu”.
Serta merta sang haji tersebut kagum dan terkejut. Betapa tidak, ia tahu persis bahwa tetangganya itu adalah orang miskin, dan terlebih lagi bahwa tahun ini ia tidak menunaikan ibadah haji.
Dengan digeluti perasaan sedih, dadanya serasa sesak, ia terbangun dari tidurnya. Sepanjang melakukan wukuf sang haji tersebut mengintrospeksi diri, memikirkan dalam-dalam apa arti di balik mimpi tersebut.
Sekembali dari Mekah, ia segera menemui tetangganya si tukang cukur. Ia menceritakan segala pengalamannya selama menunaikan ibadah haji. Tapi cerita yang paling ingin disampaikan adalah perihal diri si tukang cukur itu sendiri Dengan sikap keheranan, ia pun bertanya: “amalan apakah yang anda telah lakukan sehingga anda dianggap telah melakukan haji mabrur?”
Tetangganya pun dengan tenang bercampur haru bercerita: “bahwa sebenarnya, ia telah lama bercita-cita untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dan telah bertahun-tahun pula ia mengumpulkan biaya. Namun ketika biaya telah cukup, dan tibalah pula masa untuk berhaji, tiba-tiba seorang anak yatim tetangganya ditimpa musibah yang hampir merenggut jiwanya. Maka si tukang cukur termaksud menyumbangkan hampir keseluruhan biaya yang telah bertahun-tahun dikumpulkan itu untuk membiayai anak yatim tersebut, sehingga ia gagal menunaikan ibadah haji”.
Sejak itu, pak haji baru sadar, bahwa ternyata kita sering salah langkah dalam upaya mencari ridha Allah. RidhaNya terkadang diburu dengan semangat egoisme yang berlebihan dan tanpa disadari justeru bertolak belakang dengan keridhaanNya. Dengan kata lain, betapa ibadah-ibadah kita sering ternoda oleh lumpur kepicikan egoisme pelakunya, jauh dari nilai-nilai “kasih sayang” (rahmatan lil’alamin).
Tidakkah terpikirkan oleh mereka yang berhaji, khususnya yang berhaji sunnah (berhaji lebih dari satu kali), akan nasib berjuta-juta anak yatim akibat “musibah” perekonomian saat ini? Akibat krisis ini telah berjuta manusia yang kehilangan “induk” (pegangan) dalam hidupnya. Atau belumkah masanya kaum Muslimin untuk meletakkan prioritas-prioritas dalam kehidupannya sebagai ummat? Kalaulah misalnya, dari sekian ribu Muslim yang berhaji sunnah (lebih dari sekali) ditunda melakukannya, dan uang ongkos haji tersebut dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak-anak ummat ini, batapa cerahnya masa depan kita.
Masalahnya, sekali lagi, sampai di mana pengaruh ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sosial kita? Mungkin para penda’i perlu kembali mensosialisasikan S. Al Maa’uun kepada ummat ini. Abu Bakar ditanya tentang haji mabrur, beliau menjawab: “Lihatlah jikalau anda telah kembali ke Madinah”. Jawaban ini membuktikan bahwa haji mabrur hanya dapat diidentifikasi pada saat pelaku haji berada di kampung halaman masing-masing. Sampai di mana “predikat haji” tersebut mampu mendongkrak kesalehan, baik dalah kehidupan fardi maupun kehidupan jama’inya.
Akhirnya, kepadaNya semata kita berserah diri. Semoga haji kita dapat merubah moralitas kita menuju pada tingkatan yang lebih ilahiyah sifatnya tanpa mengurangi rasa kepedulian terhadap “mas’uliyah ijtima’iyah” (tanggung jawab sosial) kita terhadap sesama. Dengan kata lain, semoga ibadah haji dapat mengantar pelakunya menjadi insan-insan taqi (bertakwa), tidak saja pada tataran individual namun juga pada tataran sosialnya.
M. Syamsi Ali
Sumber : http://media.isnet.org/